NEGARA kita
belakangan ini ramai dengan pro-kontra seputar perubahan kurikulum pendidikan
yang akan ditetapkan mulai tahun ajaran 2013/2014. Berbagai pendapat mengemuka,
mulai dari pakar, pengamat, hingga praktisi pendidikan. Namun, hampir dari
seluruh pendapat yang ada, semua mengarah pada hal teknis, yaitu bagaimana daya
serap tenaga pendidikan (guru) dalam menerapkan kurikulum baru itu, sementara
kurikulum lama belum terimplementasi secara utuh.
Kekhawatiran berbagai pihak
terhadap kurikulum baru itu adalah hal yang lumrah, terutama jika melihat data
empiris terhadap perubahan kurikulum yang cukup sering terjadi di negeri ini.
Dimana perubahan kurikulum tidak diikuti dengan perubahan yang diharapkan.
Rata-rata kurikulum hanya indah di atas kertas dan rapuh dalam realita. Yang
lebih parah adalah, mindsetdan metode guru
dalam pembelajaran, ternyata tidak mengalami banyak perubahan.
Di sisi lain, pemerintah
melihat perubahan tersebut sebagai kebutuhan untuk menyongsong masa depan,
demikian seperti dipaparkan oleh Muhammad Nuh selaku Kemendikbud (Kompas,
7/12). Mantan Rektor ITS itu menegaskan bahwa perubahan kurikulum bukan hal
tabu atau terlarang, justru perubahan kurikulum harus dilakukan agar sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
Perubahan kurikulum dilakukan
karena Kurikulum 2006 (Kurikulum KTSP) dianggap masih menimbulkan berbagai
fenomena negatif, seperti banyaknya mata pelajaran yang sangat membebani siswa,
sementara hampir semua mata pelajaran cenderung pada pencapaian kompetensi dan
kurang bermuatan karakter, sehingga melahirkan mental pragmatis, plagiarisme,
kecurangan, tawuran pelajar, dekadensi moral, dan pengabaian nilai dan norma
agama. Lihat saja berita terbaru di Situbondo Jawa Timur, bagaimana para
pelajar yang semestinya gemar menuntut ilmu, justru melakukan arisan bersama
untuk ‘membeli’ WTS.
Bagi umat Islam, perubahan
kurikulum 2013 cukup memberi angin segar. Pasalnya jam mata pelajaran
Pendidikan Agama rencananya akan mendapat tambahan. Untuk tingkat SD,
Pendidikan Agama kelas IV, V dan VI menjadi 4 jam. Hal ini tentu perlu
disyukuri, karena selama ini Pendidikan Agama hanya dianggap sebagai pelajaran
pelengkap semata. Semoga saja, pemerintah juga memasukkan Pendidikan Agama
sebagai mata pelajaran yang dimasukkan dalam Ujian Nasional (UN). Syukur-syukur
jika Pendidikan Agama lebih diprioritaskan untuk terbentuknya adab dalam
kehidupan bangsa dan negara. Jadi, tidak kognitif belaka, seperti selama ini
terjadi.
Ilmu yang Rusak Melahirkan Peradaban Rusak
Namun demikian, sejatinya ada
yang lebih penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen bangsa ini, terutama
Kemendikbud untuk membangun pendidikan yang benar-benar handal dari sekedar
utak-atik konsep kurikulum yang akan selalu menuai pro-kontra. Hal tersebut
adalah epistimologi atau sumber kita mencari ilmu yang akan menjadi ruh dari
kurikulum itu sendiri.
Epistemologi
berasal dari bahasa Yunani kuno, έπιστεήε yang bermakna pengetahuan dan
λογος yang artinya kata, logika, akal,
diskursus, teori. Epistemologi bermakna diskursus
ataupun teori mengenai ilmu. Dengan
perkataan lain, materi pembahasan dalam
epistemologi adalah ilmu. Dalam epistemologi,
akan dibahas misalnya, mengenai proses/cara
mendapat ilmu, sumbersumber ilmu dan klasifikasi
ilmu, teori tentang kebenaran, dan halhal lain yang terkait dengan filsafat
ilmu. (Adnin Armas,Konsep Ilmu dalam Islam)
Mari kita tengok, apa saja yang
disediakan pemerintah bagi tunas bangsa untuk membangun mental dan frame
berpikir mereka. Dari mata pelajaran Sosiologi, dari kelas X hingga XII, teori
yang dipaparkan adalah teori para pemikir Barat, yang tidak saja bertentangan
dengan falsafah dan sejarah bangsa, tetapi juga dengan nilai dan kultur negara.
Di kelas X, pelajar SMA sudah harus ‘mengunyah’ pendapat Auguste Comte yang
anti Tuhan, dan Emil Durkheim yang anti agama.
Sementara itu, dalam pelajaran
Ekonomi, mereka harus menelan doktrin Adam Smith yang menyatakan bahwa sumber
daya alam terbatas dan kebutuhan manusia tidak terbatas. Ironisnya, dari
seluruh sumber belajar untuk tingkat SMP dan SMA, tak satupun nama intelektual
Muslim disebutkan. Padahal, sejarah mencatat bahwa kemajuan Barat berawal dari
interaksi mereka dengan Peradaban Islam yang menginspirasi dunia hingga saat
ini.
Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa, pemerintah kita masih merujuk Barat sebagai sumber ilmu.
Padahal, secara epistemologis, konstruk keilmuan dari Barat bisa merusak mental
dan cara berpikir generasi bangsa. Hal ini tidak lain karena, Barat telah
mereduksi sumber ilmu hanya pada hal-hal yangobservable. Di luar
itu, seperti anggapan Immanuel Kant dan Durkheim hanyalah ilusi, mitos, dan takhayul.
Wajar jika kemudian, frame
berpikir masyarakat Indonesia umumnya pro terhadap Barat dan salah paham
terhadap Islam. Belum lagi jika melihat acuan mata kuliah Filsafat Ilmu di
tingkat perguruan tinggi. Jangankan di perguruan tinggi umum, di perguruan
tinggi Islam saja, sumber belajar yang dijadikan rujukan untuk mendidik anak
bangsa hampir semuanya dari Barat. Tidak saja kajian umum, termasuk kajian
Islam, mulai dari Studi Islam hingga tafsir al-Qur’an yang memasukkan
Hermeneutika sebagai mata kuliah wajib.
Apabila sumber ilmu ini tidak
diubah, maka perubahan kurikulum seperti apapun dan seberapa sering dilakukan
pun, tidak akan memberi dampak signifikan, terutama dalam upaya penanaman
karakter dan pembangunan mental bangsa. Seperti seorang kepala keluarga yang
ingin membangun rumah yang indah dan kuat, tetapi mengambil bahan yang tidak
tepat, tentu rumah yang terbentuk adalah rumah yang rapuh dan buruk.
Selain itu, tetapnya pilihan
menjadikan epistemologi dan sejarah Barat sebagai sumber ilmu secara otomatis
akan melahirkan sikap inferiorisme yang menganggap Barat unggul dan maju serta
layak jadi rujukan. Di sisi lain, hal tersebut juga akan menjadikan mental
berpikir bangsa ini terus-menerus terjajah oleh epistemologi Barat.
Jadi, yang mendasar untuk
dipikirkan oleh seluruh elemen bangsa adalah bagaimana membangun sumber ilmu
yang benar-benar mampu melahirkan generasi bangsa yang beriman dan bertakwa.
Tentu tidak ada cara lain, kecuali dengan kembali menerapkan sumber ilmu yang
telah menjadikan umat Islam unggul dalam memimpin peradaban selama lebih dari
tujuh abad lamanya, termasuk telah menyelamatkan Eropa dari kegelapan selama
berabad-abad.
Pemerintah harus lebih objektif
dalam melihat epistemologi Islam dan kritis terhadap epistemologi Barat. Karena
secara hakiki, bangsa dan negara ini sesungguhnya sangat membutuhkan sumber
ilmu yang benar-benar bersumber dari ajaran Islam, bukan yang lain.
Tanpa perubahan sumber ilmu secara epistemologis,
maka negeri ini hanya akan menduplikat kecanggihan teknologi yang justru
membingungkan manusia itu sendiri, sehingga lahir krisis kehidupan yang tak
terkendali. Suatu krisis yang menurut Fritjof Capra telah merusak seluruh
elemen penting kehidupan, tidak saja alam, tetapi juga intelektual dan jiwa
manusia itu sendiri, sehingga ilmu yang kini ada sama sekali tidak mampu
menjawab masalah yang dihadapi manusia.
Pakar hukum justru melanggar hukum,
pemegang amanah justru serakah, pedagang banyak yang curang, pelajar banyak
yang kurang ajar, dan rakyat banyak yang bejat. Semua ini adalah masalah yang
selamanya sulit diatasi, jika negara masih menjadikan teori dan pengalaman
Barat sebagai konsep solusi untuk membangun bangsa dan negara.
Salah satu tantangan pemikiran
Islam kontemporer yang dihadapi kaum Muslimin saat ini adalah
problem ilmu. Sebabnya, peradaban Barat yang mendominasi
peradaban dunia saat ini telah menjadikan
ilmu sebagai problematis. Selain telah salahmemahami makna ilmu,
peradaban tersebut telah menghilangkan maksud dan tujuan ilmu. Sekalipun
peradaban Barat modern telah menghasilkan ilmu yang
bermanfaat, namun, tidak dapat dinafikan bahwa
peradaban tersebut juga telah menghasilkan ilmu
yang telah merusak khususnya kehidupan spiritual manusia. Epistemologi
Barat bersumber kepada akal dan pancaindera.
Konsekwensinya,
berbagai aliran pemikiran sekular seperti
rasionalisme, empirisme, skeptisisme, relatifisme,
ateisme, agnotisme, humanisme, sekularisme, eksistensialisme,
materialisme, sosialisme, kapitalisme, liberalisme mewarnai peradaban
Barat modern dan kontemporer. Westernisasi ilmu telah menceraikan hubungan
harmonis antara manusia dan Tuhan, sekaligus telah melenyapkan Wahyu sebagai
sumber ilmu. (Adnin Armas, Konsep Ilmu dalam Islam)
Akhirul kalam,
masa depan bangsa ini selain dipengaruhi oleh struktur kurikulum, lebih jauh
sangat ditentukan oleh sumber ilmu yang dijadikan pedoman dalam mendidik
generasi masa depan. Oleh karena itu, revisi sumber ilmu adalah keniscayaan
bagi negeri ini untuk bisa eksis di masa depan. Jika tidak, maka selamanya kita
akan kehilangan adab, yang menurut Al-Attas adalah sumber dari segala kerusakan
manusia modern.
Bedanya dengan Barat, selain
pentingnya ilmu, para ulama kita juga memadukan ilmu dengan amal, fikir
dan zikir, akal dan hati. Kondisi
tersebut tampak jelas dalam contoh
kehidupan para ulama kita, seperti Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam
Bukhari. AlHakam bin Hisyam alTsaqafi mengatakan: “Orang
menceritakan kepadaku di negeri Syam, suatu
cerita tentang Abu Hanifah, bahwa beliau
adalah seorang manusia pemegang amanah yang
terbesar. Sultan mau mengangkatnya menjadi pemegang kunci gudang kekayaan
Negara atau memukulnya kalau menolak. Maka Abu Hanifah memilih siksaan
daripada siksaan Allah Ta’ala.”
Ada pula kisah Imam Syafi‘i
yang hapal al-Quran semenjak usia 9 tahun. Pada usia 10 tahun, beliau sudah
menghafal hadits yang terdapat dalam kitab Al Muwaththa karya Imam Malik. Di usianya yang 15 tahun, beliau
lulus dalam spesialisasi hadis dari gurunya Imam Sufyan bin Uyaina, sehingga
beliau diberi kepercayaan untuk mengajar dan memberi fatwa kepada masyarakat
dan menjadi guru besar di Masjidil Haram, Makkah al Mukarramah.
Bukunya Ar
Risalah dan Al 'Um banyak dirujuk. Bahkan ajaran Imam Syafi'i terkenal
dengan Mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia, Asia
Tenggara, Mesir, Baghdad, dan negara lainnya . Yang mengagumkan, ulama bernama
lengkap Muhammad Ibnu Idris bin Abbas bin Usman Asy Syafi'I selain dikenal
ulama mashur, beliau selalu menghkatamkan alQur’an dalam bulan Ramadhan,
enam puluh kali. Semuanya itu dalam shalat. Bisakah kurikulum pendidikan kita
bisa melahirkan orang-orang sekelas itu? Minimal di bawahnya?*
Penulis adalah pengasuh pesantren, tinggal di
Depok Jawa Barat



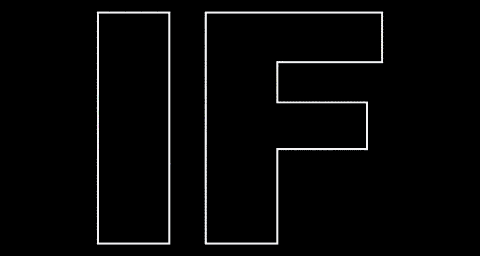
 16.50
16.50
 www.ni'am.com
www.ni'am.com


